 Athaya Nadira
Athaya Nadira
Politik | 2025-10-18 15:21:03
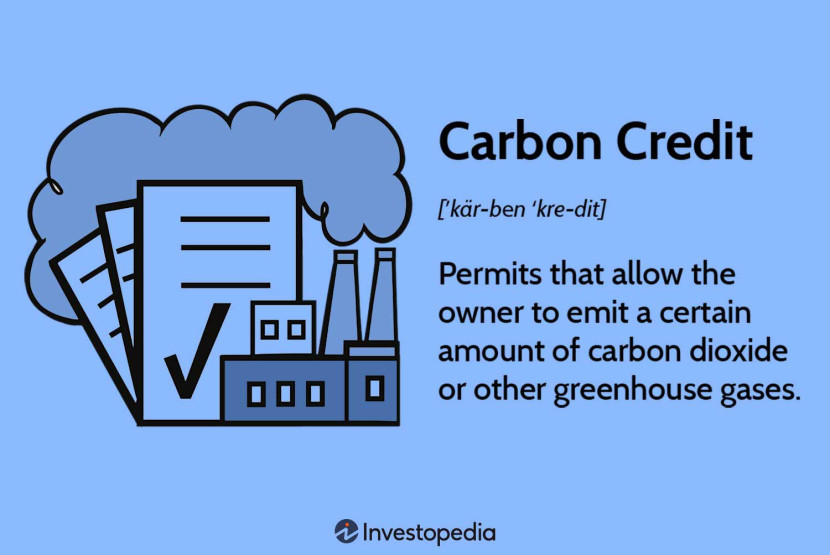
Kita udah hidup di zaman di mana krisis iklim bukan cuma headline berita, tapi realitas sehari-hari. Suhu makin ekstrem, musim nggak bisa diprediksi, dan bencana alam makin sering datang. Tapi lucunya — atau ironisnya — yang paling kena dampaknya justru negara-negara berkembang, bukan mereka yang paling banyak nyumbang emisi karbon.
Negara-negara di Eropa dan Amerika Utara udah menikmati revolusi industri sejak abad ke-18. Mereka tumbuh kaya berkat pabrik-pabrik besar yang membakar batu bara dan minyak bumi tanpa mikirin efeknya ke bumi. Sekarang, pas suhu global naik dan es kutub mencair, negara-negara di Selatan — kayak Indonesia, Bangladesh, dan Kenya — malah jadi korban paling depan. Padahal, kontribusi kita terhadap emisi global tuh cuma sebagian kecil dari mereka.
Data dari Global Carbon Project 2024 menunjukkan, sejak revolusi industri, hampir 60% total emisi karbon dunia datang dari negara-negara maju. Sementara seluruh Afrika cuma nyumbang sekitar 3%. Jadi ya, kalau bumi ini kayak rumah kos yang udah rusak, jelas yang bikin berantakan duluan bukan negara berkembang. Tapi anehnya, yang disuruh beresin rame-rame justru kita semua, seolah tanggung jawabnya setara.
Utang Karbon : Konsep yang Bikin Banyak Negara Maju Gelagapan
Istilah “utang karbon” muncul buat menggambarkan ketimpangan itu — kayak semacam tagihan moral buat negara maju yang udah terlalu lama hidup boros energi fosil. Ide dasarnya simpel: kalau lo udah menikmati manfaat ekonomi dari pembakaran karbon selama ratusan tahun, lo juga harus bayar kompensasi buat kerusakan yang sekarang ditanggung semua orang.
Wacana ini sebenernya udah lama dibahas dalam forum internasional kayak Conference of the Parties (COP). Pada COP27 di Mesir tahun 2022, akhirnya disepakati pembentukan Loss and Damage Fund — semacam dana kompensasi buat negara-negara rentan yang kena dampak parah dari krisis iklim. Tapi sampai sekarang, realisasinya masih lambat banget. Negara-negara kaya banyak yang janji doang, tapi nyumbangnya minim.
Padahal, kebutuhan dananya gila-gilaan. Menurut UNEP Adaptation Gap Report 2023, negara berkembang butuh sekitar 215 miliar dolar per tahun buat adaptasi perubahan iklim. Tapi yang beneran cair dari bantuan internasional nggak sampai 10% dari angka itu. Sementara di sisi lain, negara-negara G7 masih ngasih subsidi energi fosil hampir 1 triliun dolar per tahun. Jadi jelas, mereka masih lebih peduli jaga bisnis minyak daripada jaga planet.
Bahkan Indonesia pun udah mulai ngerasain dampaknya. Naiknya permukaan laut bikin banyak wilayah pesisir rawan tenggelam. Di Semarang, Jakarta, dan Demak, masyarakat udah hidup dengan dinding beton di depan rumah buat nahan air laut. Ironisnya, mereka harus bayar pajak dan listrik, sementara yang nyumbang emisi besar malah terus jalanin industri tanpa batas.
Kalau mau jujur, dunia udah terlalu lama hidup dalam sistem yang nggak adil. Negara kaya bilang mereka peduli lingkungan, tapi mereka juga yang paling banyak ekspor mobil bensin, buka tambang batu bara di luar negeri, dan ngegasin produksi industri yang rakus energi. Jadi kalau ngomong soal “transisi energi bersih”, ya harusnya mereka yang paling duluan berubah — dan bantu negara berkembang ikut pindah jalur tanpa bikin ekonomi ambruk.
Indonesia misalnya, lagi di posisi dilematis. Kita masih butuh energi fosil buat ngejar pembangunan, tapi juga ditekan buat nurunin emisi. Target Net Zero Emission 2060 udah diumumkan, tapi buat nyampe ke sana perlu investasi ratusan miliar dolar. Kalau negara maju beneran mau tanggung jawab, mestinya mereka bantu bukan cuma lewat janji pendanaan, tapi juga lewat transfer teknologi, penghapusan utang hijau, dan pasar karbon yang adil.
Masalahnya, mekanisme global masih berat sebelah. Banyak proyek hijau diatur supaya investor dari negara maju tetap untung, sementara negara berkembang cuma jadi penyedia lahan atau tenaga kerja murah. Konsep keadilan iklim (climate justice) akhirnya kehilangan makna kalau semuanya masih berpusat pada kepentingan ekonomi negara kaya.
Tapi bukan berarti negara berkembang cuma bisa nunggu belas kasihan. Negara-negara G77, termasuk Indonesia, udah mulai bersuara keras di forum internasional. Mereka minta sistem pendanaan yang lebih transparan dan berbasis tanggung jawab historis. Artinya: negara kaya harus bayar lebih besar, bukan karena mereka dermawan, tapi karena mereka memang punya utang ekologis terhadap dunia.
Krisis iklim ini nggak bisa ditangani pakai narasi “kita semua sama-sama bersalah”. Nggak, kita nggak semua sama. Ada yang udah lama boros, ada yang baru bisa nyalain listrik 10 tahun lalu. Ada yang bangun pabrik di mana-mana, ada yang masih struggling nyari air bersih. Kalau solusi iklim global nggak ngakuin ketimpangan itu, ya yang bakal menang lagi-lagi cuma mereka yang udah kaya dari polusi.
Sekarang waktunya tagihan itu dibayar. Negara maju harus berhenti pura-pura buta soal utang karbonnya. Bumi bukan cuma korban dari industrialisasi tanpa batas — tapi juga saksi betapa keserakahan bisa disamarkan jadi “pembangunan”. Kalau dunia mau tetap layak huni buat generasi berikutnya, keadilan iklim harus mulai dari pengakuan siapa yang paling banyak berutang, dan siapa yang paling pantas menagihnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

 4 months ago
77
4 months ago
77

















































