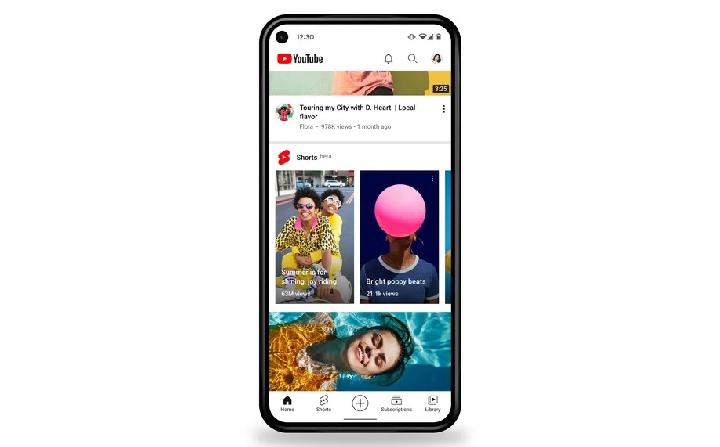TEMPO.CO, Jakarta - Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia (UII) Listya Endang Artiani menyoroti fenomena perilaku masyarakat yang berbondong-bondong membeli emas di saat harganya justru naik. Listya mengatakan, tak sedikit masyarakat yang memborong emas hanya sekadar ikut-ikutan maupun fear of missing out alias FOMO.
“Fenomena aksi borong emas saat harga sedang tinggi merefleksikan adanya bias kognitif seperti herding behavior—perilaku ikut-ikutan—dan FOMO atau ketakutan akan kehilangan peluang yang sedang dinikmati orang lain,” kata dia dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Senin, 21 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun dalam beberapa pekan terakhir, dunia dikejutkan oleh lonjakan harga emas. Pada awal April, harganya sekitar 3.350 dolar Amerika Serikat (AS) per ons troy atau per 31,1 gram. Berdasarkan nilai tukar rupiah ke dolar AS di Rp 16,800-an, maka per gramnya harga emas mencapai sekitar Rp 1,8 jutaan.
Menurut Listya, kenaikan harga emas dengan rekor tertinggi sepanjang sejarah ini mencerminkan gejolak global yang semakin intens. Mulai dari ekspektasi penurunan suku bunga The Federal Reserve, memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur, hingga pelemahan dolar Amerika Serikat yang berkepanjangan.
Masyarakat lantas ramai-ramai membeli emas di saat harganya melonjak sebagai bentuk perlindungan nilai (store of value). Menurut Listya, fenomena ini terjadi lantaran emas bisa menjadi safe haven asset yang mampu mempertahankan nilainya ketika terjadi tekanan sistemik pada pasar keuangan.
“Secara teoritis, kondisi ini memperkuat fungsi emas sebagai safe haven asset, yakni aset yang dicari saat risiko sistemik meningkat,” kata dia.
Namun, menurut Listya, kenaikan harga emas tidak semata-mata didorong oleh perhitungan rasional berbasis nilai intrinsik atau teori portofolio saja. Tetapi berdasarkan pendekatan behavioral economics, kata dia, juga oleh perilaku psikologis investor yang sering kali menyimpang dari logika ekonomi konvensional.
Pengajar di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII, Yogyakarta, ini menjelaskan, ketika harga emas mencetak rekor demi rekor, investor—dalam hal ini masyarakat—cenderung menganggap tren akan terus berlangsung. Akibatnya, keputusan membeli emas lebih didorong oleh tekanan sosial dan sinyal pasar ketimbang analisis fundamental.
Listya berpendapat, tren ramai-ramai beli emas sejalan dengan temuan Shiller pada 2015, yang menyatakan bahwa sentimen kolektif pasar sangat berpengaruh dalam membentuk gelembung aset (asset bubbles). Menurut dia, fenomena ini disebut extrapolation bias, kecenderungan memperkirakan masa depan hanya berdasarkan data masa lalu jangka pendek.
Lebih lanjut, Listya mengatakan fenomena ini juga bisa dijelaskan melalui konsep loss aversion dari teori prospek (prospect theory) oleh Kahneman dan Tversky. Dalam teori tersebut, dijelaskan bahwa investor cenderung lebih takut mengalami kerugian ketika inflasi meningkat atau krisis global membayangi, dibandingkan keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan.
“Investor mencari instrumen yang dirasa aman dan emas, sebagai simbol kestabilan, menjadi pilihan intuitif. Dalam situasi seperti ini, keputusan membeli emas bahkan ketika harganya tinggi merupakan bentuk dari keengganan menghadapi kerugian nilai riil dari aset lain,” kata dia.
Menurut Listya, data juga mendukung pola perilaku ini. Menurut laporan Google Trends dan media investasi digital seperti CNBC dan Bloomberg selama Maret–April 2025, pencarian daring tentang “beli emas sekarang” dan “emas naik terus” meningkat lebih dari 200 persen. Hal ini mencerminkan gelombang minat spontan dari masyarakat luas, bukan hanya investor profesional, terhadap emas sebagai instrumen lindung nilai.
“Pada saat yang sama, media sosial turut memperkuat efek confirmation bias, dimana narasi-narasi optimis terhadap emas tersebar luas dan memperkuat keputusan emosional kolektif.
Implikasinya, kata Listya, keputusan investasi masyarakat sering kali berada di persimpangan antara logika dan psikologi. Dalam konteks ini, penting bagi pembuat kebijakan dan otoritas keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar keputusan investasi lebih berdasar dan berjangka panjang. Bukan sekadar respons emosional terhadap gejolak sesaat di pasar.