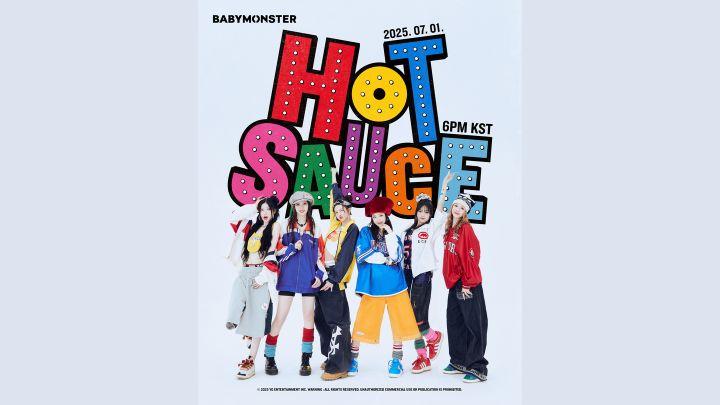(Beritadaerah-Kolom) Semarang, 2038. Pabrik itu dulu hanya gudang berdebu di ujung kota. Pelat besi menumpuk, mesin bubut tua berdenting tak tentu, dan pegawainya tak lebih dari 40 orang. Sebagian besar tak pernah berpikir akan bekerja dengan robot kolaboratif atau membuat komponen kendaraan listrik untuk pasar Filipina. Tapi hari ini, tempat itu penuh layar sentuh, sensor presisi, dan tim riset kecil di lantai dua yang dulunya gudang kayu.
Perusahaan ini milik Pak Harsono, lulusan SMK teknik yang mewarisi bisnis onderdil dari ayahnya. Dulu mereka hanya melayani toko-toko motor di sekitar Jawa Tengah. Tapi pada 2027, Harsono memutuskan ikut program kemitraan manufaktur dari pemerintah pusat. Awalnya ia skeptis, lalu ia coba pelatihan otomasi dasar, lalu digitalisasi rantai pasok. Kini perusahaannya punya 200 karyawan dan 60 persen pendapatannya dari ekspor.
Kisah seperti ini bukan satu-dua. Mereka tumbuh di berbagai sudut Indonesia, dari pabrik tahu bertenaga surya di Kendari, sampai petani rempah digital di Sigi. Tapi tidak semua semulus cerita Harsono.
Di sisi lain negeri, di Labuan Bajo, komunitas nelayan juga sedang naik kelas. Dulu mereka hanya menjual ikan ke tengkulak. Lalu koperasi lokal bekerja sama dengan perusahaan teknologi dari Bandung. Mereka buat sistem pemesanan daring untuk wisata bahari, melatih warga jadi pemandu selam, dan memberi akses ke pendanaan mikro. Empat tahun kemudian, penghasilan komunitas melonjak. UMKM makanan, kerajinan, dan transportasi lokal ikut tumbuh.
Transformasi itu bukan sulap. Ia lahir dari kombinasi lima hal: modal keuangan yang cair, manusia yang terlatih, institusi yang melayani, infrastruktur yang menghubungkan, dan kewirausahaan yang berani. Lima fondasi yang disebut 5I dalam berbagai laporan pembangunan.
Tapi tantangan tetap datang. Di sektor pertanian, petani masih terjebak di lahan sempit dan teknologi lama. Rata-rata mereka mengelola 0,6 hektar—kebanyakan tanpa irigasi modern. Hanya 2 persen petani yang terhubung dengan e-commerce. Padahal jika diberi teknologi, benih unggul, dan akses pasar langsung, produktivitas bisa melonjak.
Urbanisasi pun jadi pisau bermata dua. Di satu sisi membawa tenaga kerja ke pusat pertumbuhan, di sisi lain menumpuk kemiskinan di pinggiran kota. Konsep kota 15 menit menjadi jawaban: membangun lingkungan tempat tinggal yang dekat dengan fasilitas kerja, pendidikan, dan layanan publik. Di Surabaya, Bandung, dan Makassar, konsep ini mulai terlihat nyata.
Namun yang tak kalah penting adalah menyederhanakan proses berusaha. Pada 2023, butuh 43 hari dan biaya lebih dari US$1.000 untuk mendirikan perusahaan formal. Kini, di tahun 2040-an, hanya butuh empat hari lewat aplikasi terpadu. Hal kecil seperti ini yang membuat ribuan usaha mikro akhirnya berani naik kelas.
Perusahaan besar menjadi jangkar. Mereka menyerap tenaga kerja, membuka pelatihan, dan mendorong transformasi usaha kecil yang berada di sekitarnya. Tapi esensi keberhasilan Indonesia bukan di sana. Ia terletak pada keberanian kolektif jutaan pelaku usaha yang memutuskan untuk berubah—dari informal ke formal, dari statis ke adaptif.
Indonesia bukan lagi hanya negeri ribuan pulau. Ia menjadi jaringan ribuan simpul produktif, yang tumbuh bersama, saling menguatkan, dan menolak tertinggal.
Kini, ketika dunia menengok ke Asia Tenggara, Indonesia bukan hanya besar. Ia cerdas, tangguh, dan setara. Bukan lagi archipelago economy, tapi enterprising archipelago—tempat di mana setiap orang, dari kota hingga pelosok, bisa ikut membangun masa depan bersama.
Tak jauh dari perbatasan Kalimantan Utara, di sebuah kecamatan bernama Malinau, seorang anak muda bernama Yayan baru saja membuka bengkel digital. Dulu ia hanya teknisi panggilan, mengandalkan jaringan WhatsApp untuk mencari pelanggan. Tapi ketika sebuah perusahaan besar otomotif membuka pusat pelatihan di Tarakan, Yayan ikut. Ia belajar tentang otomasi kendaraan listrik dan pemetaan komponen pintar. Setahun kemudian, ia kembali ke kampung dan membangun bengkel dengan sistem antrean daring, menerima pembayaran dengan dompet digital, dan menjadi mitra rantai pasok suku cadang untuk kawasan timur.
“Dulu saya cuma tukang servis keliling, sekarang saya punya invoice mingguan dan laporan keuangan,” katanya sambil tertawa, bangga. Yang berubah bukan hanya status usahanya, tapi juga cara dia melihat masa depan.
Transformasi seperti ini terjadi karena ekosistemnya dibenahi. Perusahaan besar tidak lagi berdiri sendiri, tetapi mengalirkan keahliannya ke usaha yang lebih kecil. Lembaga keuangan mikro tidak sekadar menyalurkan pinjaman, tapi juga pendampingan. Inkubator bisnis tidak hanya memberi ruang kerja bersama, tapi menjadi pintu masuk ke jaringan nasional.
Namun perubahan besar seperti ini tidak bisa terjadi hanya dari atas. Di desa-desa pesisir Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, komunitas perempuan nelayan membentuk koperasi pengolahan hasil laut. Mereka tidak hanya menjual ikan, tapi memproduksi kerupuk udang organik dan abon tuna dalam kemasan vakum. Salah satu anggota koperasi, Ibu Rasti, bercerita bagaimana ia belajar membuat barcode produk dan mendaftarkan usaha ke sistem OSS (Online Single Submission). Anaknya yang kuliah di Kupang membantu membuatkan katalog digital. Kini, produknya masuk ke platform dagang nasional.
“Waktu saya muda, tidak pernah mimpi bisa kirim produk sampai ke Jakarta,” ujarnya sambil menunjukkan lembar pesanan dari pelanggan di Bekasi.
Cerita-cerita seperti ini yang menghidupkan angka-angka makro. Ketika laporan menyebut bahwa hanya 0,3 perusahaan formal baru per 1.000 penduduk usia kerja lahir setiap tahun, itu artinya ada tembok besar yang menghalangi niat jadi pengusaha formal. Dan ketika program-program mulai mengikis hambatan itu—dari perizinan cepat, pembiayaan awal, hingga pengurangan biaya legal—maka ribuan usaha kecil mulai bermigrasi dari informal ke formal.
Sektor pertanian pun mulai berubah. Di Sumedang, para petani muda kini memanfaatkan sensor tanah untuk mengatur kelembaban dan nutrisi lahan. Mereka menggunakan drone penyemprot, menghitung musim tanam berdasarkan prediksi cuaca dari aplikasi iklim, dan menjual panen langsung ke koperasi konsumen di Jakarta tanpa perantara. Ini bukan revolusi satu malam, tapi buah dari dekade pelatihan, penguatan institusi lokal, dan akses terhadap infrastruktur dasar seperti internet dan listrik stabil.
Meski begitu, tantangan tetap banyak. Masih ada 80 persen desa yang belum memiliki layanan keuangan lengkap. Masih banyak sekolah vokasi yang kekurangan peralatan dan pengajar industri. Masih sering usaha kecil merasa kalah bersaing dengan perusahaan besar karena kurang informasi dan standar mutu. Namun, semakin jelas bahwa arah kebijakan hari ini memberi ruang agar semua pemain bisa bertumbuh bersama.
Pemerintah belajar dari banyak negara. Di Korea Selatan, pertumbuhan perusahaan menengah mendorong penciptaan kelas menengah produktif. Di Polandia, urbanisasi diiringi dengan pelatihan kerja terintegrasi. Di Brasil, koperasi menjadi tulang punggung ekspor pangan olahan. Indonesia mengambil pelajaran, menyesuaikan dengan lokalitas, dan menjalankan skenario sendiri—yang tidak meniru sepenuhnya, tapi juga tidak berpangku tangan.
Kembali ke Semarang, Harsono kini sedang memperluas pabriknya. Ia ingin menambah lini produksi untuk komponen sepeda listrik. Ia sudah menandatangani kerja sama dengan startup mobilitas dari Vietnam. Tapi saat ditanya apa kunci keberhasilannya, ia menjawab singkat, “Kami hanya perusahaan kecil yang diberi kesempatan untuk tumbuh.”