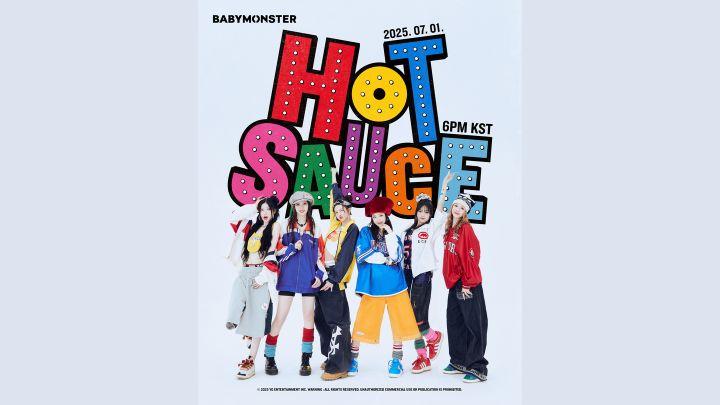(Beritadaerah – Kolom)Bayangkan sebuah hari ketika bumi tidak lagi diam. Langit bukan hanya biru atau kelabu, tetapi juga punya harga. Setiap hembusan asap dihitung, setiap daun yang tumbuh di hutan punya nilai, dan setiap tetes karbon yang tidak dilepas ke atmosfer dianggap sebagai investasi untuk masa depan. Dunia tidak lagi berjalan seperti dulu. Ia mulai menimbang bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga stabilitas iklim. Dan dari sinilah, lahir apa yang kini disebut sebagai perdagangan karbon—sebuah sistem yang mencoba menyatukan logika lingkungan dan logika pasar ke dalam satu mekanisme bersama.
Perubahan iklim bukan sekadar ancaman lingkungan, tapi juga risiko nyata bagi sistem keuangan global. Ketika badai melumpuhkan pelabuhan, kekeringan mengancam ketahanan pangan, atau kebakaran hutan menghancurkan infrastruktur, dampaknya menyentuh seluruh rantai ekonomi. Bank bisa rugi besar, perusahaan bisa gagal bayar, dan nilai investasi bisa jatuh. Tak heran, lembaga keuangan mulai memperhitungkan risiko ini dalam setiap keputusan bisnis mereka. Bukan lagi cukup melihat laporan keuangan—mereka juga harus melihat peta risiko iklim.
Namun di balik risiko, ada peluang besar. Transisi menuju ekonomi rendah karbon menciptakan kebutuhan akan pembiayaan baru. Dunia butuh energi bersih, transportasi hijau, dan teknologi yang ramah lingkungan. Semua itu membutuhkan investasi. Di sinilah peran sektor jasa keuangan menjadi sangat strategis: mereka bisa menjadi jantung dari revolusi hijau, bukan hanya menyediakan uang, tetapi juga arah dan komitmen. Dan yang lebih penting, mereka bisa membuat penyelamatan lingkungan menjadi sesuatu yang menguntungkan.
Dunia telah bersatu dalam satu tujuan besar: mencegah bumi memanas lebih dari 1,5 derajat Celsius. Komitmen ini tidak hanya menjadi cita-cita moral, tapi juga target resmi dalam kesepakatan global seperti Paris Agreement. Negara-negara saling berjanji, dan di antara mereka, Indonesia menjadi salah satu yang menyatakan akan menurunkan emisi secara signifikan. Tapi janji saja tidak cukup. Harus ada sistem yang memungkinkan pengurangan emisi terjadi dalam skala besar, cepat, dan efisien. Maka muncullah gagasan tentang nilai ekonomi karbon—bahwa setiap emisi yang dicegah atau diserap bisa dihitung dan diperdagangkan.
Dalam sistem ini, karbon menjadi komoditas. Mereka yang berhasil menurunkan emisi bisa menjual kreditnya. Mereka yang belum mampu memenuhi target bisa membelinya sambil memperbaiki proses internal. Perdagangan karbon menjadi jembatan antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. Negara seperti Indonesia, dengan kekayaan alam dan potensi proyek hijau yang luas, bisa menjadi pemain penting dalam pasar ini—bukan hanya karena kebutuhan, tapi karena peluangnya begitu besar.
Agar semua itu berjalan, sektor jasa keuangan harus ikut serta. Mereka bukan hanya penonton, tapi juga pelaku utama. Mereka bisa menyalurkan kredit hijau, mendanai proyek reforestasi, membeli obligasi berkelanjutan, atau bahkan ikut menciptakan produk keuangan berbasis emisi. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, lembaga keuangan bisa mengalihkan arus dana dari yang merusak bumi ke yang menjaga bumi. Ini bukan sekadar tren, tapi kebutuhan zaman.
Indonesia sudah mulai melangkah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 sebagai dasar hukum perdagangan karbon. OJK sebagai regulator sektor keuangan mulai menyusun panduan keuangan berkelanjutan. Dan yang paling penting, bursa karbon resmi Indonesia telah dibuka, menjadi tempat di mana kredit karbon bisa diperdagangkan secara sah dan transparan. Semuanya dilakukan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan inklusivitas.
Namun membangun pasar karbon tidak sesederhana menjual barang di toko. Ada banyak lapisan yang harus disusun. Setiap proyek yang menghasilkan kredit karbon harus diverifikasi oleh pihak independen. Mereka harus membuktikan bahwa pengurangan emisi itu nyata, terukur, dan permanen. Lalu, data dari proyek itu dicatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN-PPI) agar tidak ada manipulasi atau duplikasi. Hanya yang tercatat yang bisa masuk ke pasar. Di sinilah kepercayaan publik dibangun.
Pasar karbon Indonesia terbagi dalam dua kategori: pasar wajib dan pasar sukarela. Pasar wajib berlaku bagi sektor-sektor yang ditetapkan pemerintah, seperti energi dan industri, yang harus menurunkan emisi sesuai batas tertentu. Jika mereka tidak bisa mencapai target, mereka wajib membeli kredit dari pihak lain. Sementara pasar sukarela terbuka untuk perusahaan atau lembaga yang ingin menunjukkan komitmen lingkungan, walau tidak diwajibkan. Pasar ini penting untuk mendorong kesadaran dan partisipasi luas, termasuk dari sektor swasta dan komunitas.
Tidak berhenti di situ, ada pula dimensi internasional. Negara-negara maju yang ingin memenuhi target iklimnya bisa membeli kredit karbon dari negara berkembang seperti Indonesia. Selama proyeknya sah dan terverifikasi, kredit itu bisa digunakan untuk membantu negara lain mencapai target Net Zero Emission. Ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjual “udara bersih” ke dunia, tentu dengan pengawasan yang adil dan bagi hasil yang setara.
Di balik semua itu, berdirilah sebuah ekosistem yang kompleks. Ada pemilik proyek yang melakukan aksi nyata di lapangan, ada pembeli yang membutuhkan kredit karbon, ada lembaga verifikasi yang memeriksa, ada regulator yang mengawasi, dan ada bursa yang mencatat dan memperdagangkan. Semuanya saling terhubung. Jika satu bagian gagal, sistem bisa runtuh. Maka transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci.
Proyek karbon juga tidak boleh hanya fokus pada angka. Mereka harus mempertimbangkan keadilan sosial dan hak masyarakat lokal. Hutan yang dijadikan proyek harus melibatkan warga sekitar. Jangan sampai karbon diselamatkan, tapi manusia dikorbankan. Itulah sebabnya ada standar keberlanjutan yang mencakup aspek sosial dan budaya, bukan hanya lingkungan.
Perdagangan karbon di Indonesia dilakukan dalam dua tahap, pasar primer dan pasar sekunder. Di pasar primer, kredit karbon dijual langsung dari proyek ke pembeli pertama. Di pasar sekunder, kredit itu bisa diperjualbelikan kembali seperti halnya saham. Harga bisa naik-turun tergantung permintaan pasar, kualitas proyek, dan situasi ekonomi global. Semua transaksi itu tercatat dalam sistem registri untuk memastikan keabsahan dan menghindari spekulasi liar.
Ini bukan pasar yang sederhana. Tapi jika dikelola dengan baik, ia bisa menjadi alat yang ampuh untuk mengubah arah ekonomi. Dari yang sebelumnya menghargai emisi, menjadi menghargai pengurangannya. Dari yang dulu merusak, menjadi menjaga.
Bayangkan jika setiap desa yang menjaga hutan bisa mendapat penghasilan tetap dari pasar karbon. Jika setiap perusahaan energi membangun pembangkit surya bukan karena subsidi, tapi karena menguntungkan. Jika setiap lembaga keuangan merasa rugi jika tidak masuk ke proyek hijau. Maka transisi menuju masa depan rendah karbon akan lebih cepat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan.
Dunia sedang bergerak ke arah itu. Dan Indonesia sedang membangun jalannya. Kita belum sempurna, masih banyak tantangan: dari kapasitas teknis, literasi pelaku, hingga kebutuhan investasi. Tapi langkah sudah dimulai. Dan waktu tak menunggu.
Saat langit mulai dihitung, dan hutan mulai dihargai, kita sedang menyaksikan lahirnya ekonomi baru. Ekonomi yang tak lagi mengukur kemajuan dari seberapa banyak kita membakar, tapi dari seberapa banyak kita menyelamatkan. Ini bukan sekadar ide, ini adalah jalan masa depan. Dan kita, semua yang tinggal di bumi ini, punya bagian di dalamnya.