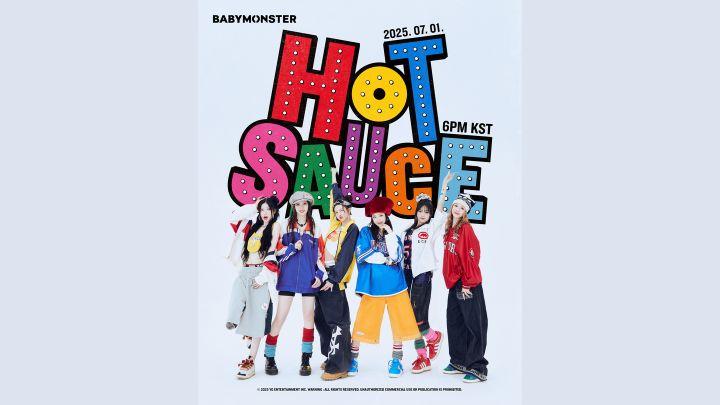(Beritadaerah – Kolom) Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatan mental telah bertransformasi menjadi isu publik yang makin mendapatkan sorotan. Tak hanya dari sisi medis, tetapi juga dari sisi sosial dan kebijakan. Indonesia pun tidak terkecuali. Data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa masalah perilaku dan emosional bukan lagi persoalan individu, melainkan persoalan bersama yang menuntut pemahaman lintas sektor dan penanganan komprehensif.
Tanda-tanda perubahan ini terlihat dari minat masyarakat terhadap topik kesehatan mental yang melonjak secara drastis sejak pandemi COVID-19 merebak. Melalui pantauan dari Indeks Google Trends, diketahui bahwa pencarian informasi terkait kesehatan mental di mesin pencari Google meningkat pesat, khususnya sejak akhir 2019 hingga pasca-pandemi. Kata kunci seperti “merasa sendiri”, “cemas”, “takut”, dan “mudah marah” menunjukkan bahwa keresahan emosional telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Bahkan setelah pandemi mereda, tren pencarian tetap tinggi. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental telah meningkat, meski belum tentu sejalan dengan kemudahan akses layanan yang mereka butuhkan.
Kondisi ini diperkuat dengan data statistik resmi yang menunjukkan peningkatan nyata dalam prevalensi kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri. Pada tahun 2024, peningkatan kasus mencapai 21,73 persen dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara menjadi daerah dengan angka kejadian tertinggi. Provinsi Papua Pegunungan mencatat hampir separuh dari seluruh kasus bunuh diri yang terjadi di wilayah Papua. Ironisnya, daerah-daerah ini adalah wilayah dengan tingkat ketersediaan layanan kesehatan mental yang sangat terbatas.
Ketimpangan akses terhadap layanan ini menjadi sorotan penting. Di Papua, hanya terdapat 0,17 fasilitas kesehatan mental per 100.000 penduduk, sangat jauh di bawah median global 1,3 menurut World Health Organization. Bahkan di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang dianggap lebih maju, rasio fasilitas hanya mencapai 0,87 per 100.000 penduduk. Ketimpangan ini semakin terasa karena hampir seluruh fasilitas yang ada terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sebanyak 93 persen fasilitas kesehatan jiwa berada di kota, sementara hanya 6,78 persen yang tersebar di perdesaan. Padahal, prevalensi penderita masalah perilaku dan emosional, serta kasus bunuh diri, justru lebih banyak terjadi di desa-desa dan wilayah miskin.
Berbagai faktor sosial dan ekonomi menjadi latar belakang dari masalah kesehatan mental di Indonesia. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2023 menunjukkan bahwa individu yang bekerja di sektor pertanian dan pertambangan, memiliki tingkat pendidikan rendah, tinggal di desa, dan mengalami kesulitan akses pangan merupakan kelompok yang paling banyak mengalami masalah perilaku dan emosional. Ini berkorelasi kuat dengan teori transformasi struktural yang menyatakan bahwa kesejahteraan cenderung meningkat ketika masyarakat beralih dari sektor padat karya ke sektor keterampilan tinggi seperti industri dan jasa.
Pendidikan menjadi faktor penting yang dapat melindungi individu dari tekanan psikologis. Data menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin rendah kemungkinannya mengalami masalah perilaku dan emosional. Hal ini dapat dijelaskan karena pendidikan memberi akses pada pekerjaan yang lebih stabil, lingkungan sosial yang lebih suportif, serta keterampilan untuk mengelola stres dan tekanan hidup.
Status dalam rumah tangga juga memegang peranan signifikan. Kepala rumah tangga, terutama yang sekaligus menjadi penanggung pembiayaan terbesar, memiliki risiko lebih tinggi mengalami tekanan emosional. Tanggung jawab finansial yang besar, ditambah tekanan sosial sebagai pencari nafkah utama, menjadi beban tersendiri yang tidak semua individu siap menanggungnya. Mereka yang tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial atau jaminan kerja lebih berisiko mengalami masalah kesehatan mental.
Status perkawinan ternyata juga menjadi indikator penting. Individu yang berstatus cerai hidup atau cerai mati menunjukkan angka gangguan emosional yang lebih tinggi dibanding mereka yang menikah atau belum menikah. Studi internasional membenarkan temuan ini. Perceraian sering kali disertai rasa kehilangan, konflik, dan perasaan kesepian yang mendalam. Jika tidak ada dukungan sosial yang memadai, kondisi ini dapat dengan mudah berkembang menjadi depresi atau gangguan emosional lainnya.
Perempuan juga ditemukan lebih rentan terhadap masalah emosional dibanding laki-laki. Studi-studi menyebutkan bahwa perempuan cenderung lebih sensitif terhadap tekanan lingkungan, terutama dalam peran pengasuhan anak, konflik rumah tangga, dan kehilangan orang terdekat. Kecenderungan untuk menyimpan perasaan dan rendahnya akses terhadap dukungan psikologis membuat banyak perempuan berjuang dalam kesunyian.
Dalam aspek pekerjaan, waktu kerja juga menjadi faktor penting. Pekerja dengan jam kerja di bawah 40 jam atau di atas 42 jam per minggu menunjukkan prevalensi gangguan emosional yang lebih tinggi dibanding mereka yang bekerja dalam jam kerja normal. Waktu kerja yang terlalu pendek sering kali mencerminkan ketidakstabilan kerja, sementara jam kerja yang terlalu panjang bisa menyebabkan kelelahan mental dan fisik yang menumpuk.
Lingkungan tempat tinggal turut memainkan peran krusial. Daerah dengan pemukiman kumuh, kemiskinan tinggi, dan infrastruktur sosial yang minim memiliki prevalensi kasus bunuh diri lebih besar dibanding wilayah yang lebih sejahtera. Data dari PODES 2024 menunjukkan bahwa desa atau kelurahan yang memiliki lebih dari 75 penerbitan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dalam setahun juga memiliki tingkat kejadian bunuh diri yang tinggi. Hal ini menunjukkan korelasi kuat antara kemiskinan dan tekanan mental.
Tempat ibadah menjadi salah satu titik terang dalam upaya mendekatkan layanan psikologis ke masyarakat. Di Papua, Maluku, dan Maluku Utara, sejumlah gereja mulai menyediakan layanan konseling yang bisa diakses oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan peran penting pemuka agama sebagai penjaga kesehatan spiritual sekaligus penyambung tangan negara dalam memberikan ketenangan batin di tengah keterbatasan fasilitas medis.
Sayangnya, walaupun wilayah yang memiliki tempat ibadah lebih banyak, ternyata prevalensi bunuh diri juga tinggi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur tempat ibadah tidak serta merta menjamin bahwa nilai-nilai religius mampu menahan dorongan bunuh diri. Oleh karena itu, peran tempat ibadah perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih sistematis, termasuk pelatihan konseling dasar bagi pemuka agama dan penyediaan materi edukasi kesehatan mental berbasis spiritualitas.
Untuk memahami faktor-faktor yang paling memengaruhi kondisi emosional masyarakat, studi ini juga menggunakan pendekatan pohon keputusan. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan adalah variabel pertama yang memisahkan kelompok rentan dan tidak rentan. Mereka yang berpendidikan rendah lebih mungkin terdampak oleh ketidakpastian ekonomi, sementara mereka yang berpendidikan menengah ke atas cenderung lebih stabil secara emosional—kecuali jika mengalami krisis relasional seperti perceraian.
Analisis lanjutan menggunakan regresi logistik membuktikan bahwa pekerja informal, seperti buruh tidak dibayar atau pekerja bebas, memiliki peluang hingga 82 persen lebih tinggi mengalami masalah perilaku dan emosional dibanding pekerja tetap. Kekhawatiran terhadap ketidakcukupan pangan juga terbukti memiliki dampak signifikan. Individu yang khawatir tidak bisa makan dalam waktu dekat memiliki kemungkinan dua kali lipat mengalami tekanan emosional dibanding mereka yang tidak memiliki kekhawatiran tersebut.
Dalam konteks regional, ketimpangan antarwilayah menjadi masalah serius. Sementara kota-kota besar memiliki konsentrasi fasilitas kesehatan jiwa, daerah-daerah terpencil seperti kabupaten di Papua, Maluku, dan NTT sangat kekurangan tenaga ahli, rumah sakit jiwa, maupun fasilitas rujukan. Bahkan ketika ada fasilitas medis, beban biaya dan jauhnya jarak membuat layanan ini tidak terjangkau oleh mayoritas masyarakat desa. Hambatan geografis, budaya, dan finansial menciptakan jurang yang dalam dalam akses pelayanan kesehatan mental.
Dari kompleksitas data ini, menjadi jelas bahwa kesehatan mental di Indonesia tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah klinis atau individu. Ini adalah cerminan dari ketimpangan struktural, tekanan sosial-ekonomi, serta lemahnya sistem dukungan sosial. Penanganannya pun harus melibatkan banyak sektor: dari pemerintah, lembaga keagamaan, dunia pendidikan, hingga komunitas lokal.
Solusi yang bersifat satu dimensi, seperti hanya menambah rumah sakit jiwa di kota besar, tidak akan menyelesaikan persoalan di lapangan. Diperlukan pendekatan berbasis komunitas yang inklusif, adaptif, dan memberdayakan. Tempat ibadah bisa difungsikan sebagai pusat edukasi kesehatan mental, kepala desa dapat dilibatkan dalam deteksi dini, dan tenaga pengajar bisa diberikan pelatihan dasar tentang isu psikologis.
Pendidikan kesehatan mental juga perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sejak dini. Anak-anak harus dibekali pemahaman tentang emosi, stres, dan cara sehat menanganinya. Mereka perlu tahu bahwa meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan langkah berani untuk pulih. Di sisi lain, program perlindungan sosial harus dirancang untuk tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga dukungan psikososial yang berkelanjutan.
Masalah perilaku dan emosional di Indonesia bukan sekadar statistik. Ia adalah potret sunyi dari masyarakat yang tengah berjuang mengarungi kehidupan. Menyadari kerentanannya berarti membuka jalan bagi keberpihakan. Dan keberpihakan itu harus hadir dalam kebijakan, dalam pelayanan, dan dalam perhatian kolektif bangsa ini.