TEMPO.CO, Jakarta - Setengah abad lebih telah berlalu, tetapi kekelaman Peristiwa Malari–akronim dari Malapetaka Lima Belas Januari– yang pecah pada 1974 masih harus terus dikenang. Insiden itu menjadi cerminan bagaimana budaya anarkis demonstran dan tindakan represif aparat keamanan terhadap pengunjuk rasa yang kerap terjadi sudah berlaku sejak lama.
Banyak catatan yang mengabadikan Peristiwa Malari. Salah satunya buku Seabad Kontroversi Sejarah (2007) oleh Asvi Warman Adam. Dituliskan, pecahnya prahara tak terlepas dari datangnya Perdana Menteri atau PM Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta pada 14-17 Januari tahun itu. Padahal saat itu tengah marak sentimen anti Jepang, suatu gerakan yang menolak apa pun yang berbau kerja sama dengan mantan negara kolonial itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebuah catatan bertajuk Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru Manajemen Konflik, Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok (2010) oleh Eep Saefullah Fatah mengungkapkan, malam sebelum kejadian atau pada 14 Januari 1974, ratusan mahasiswa telah berada di sekitar lapangan Halim Perdana Kusuma. Mereka berkumpul guna “menyambut” kedatangan Tanaka yang didampingi putrinya, Makiko, beserta rombongan pejabat Jepang.
Karena situasi tidak kondusif, Presiden ke-2 RI Soeharto lalu menggunakan helikopter untuk menjemput rombongan Tanaka. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak diduga oleh para mahasiswa. Sebab mereka berencana mencegat Soeharto dan Tanaka di daerah bandara sebelum menuju istana untuk menyampaikan aspirasi.
Mahasiswa sangat kecewa karena gagal. Tujuan mereka untuk menemui Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Tanaka sebenarnya untuk menyampaikan tiga tuntutan rakyat atau Tritura. Tuntutan itu yakni ihwal pembubaran asisten pribadi, penurunan harga-harga barang, dan pemberantasan korupsi.
Malam itu juga mereka berkumpul di kampus Universitas Indonesia atau UI. Diskusi ini dipimpin Hariman Siregar. Pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk mengumpulkan masa mahasiswa dalam rencana gerakan esok paginya. Bambang Sulistomo dan Theo Sambuaga ditunjuk sebagai koordinator aksi dari dewan mahasiswa UI. Kemudian. Universitas Trisakti diputuskan sebagai titik awal gerakan.
Aksi yang telah direncanakan itu pun kemudian dijalankan pada 15 Januari 1974. Sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, massa akan berkumpul di lapangan Monumen Nasional atau Monas. Massa pimpinan Bambang Sulistomo dan Theo Sambuaga itu berkumpul dulu di halaman UI sekitar pukul 08.00 WIB sebelumnya lalu bergerak ke titik awal aksi di Trisakti.
Tak ada yang menyana rencana demonstrasi itu jadi huru-hara. Dalam perjalanan menuju kampus Trisakti telah terjadi beberapa perkembangan. Pertama, semakin lama massa makin bertambah oleh bergabungnya massa yang telah menunggu di jalanan antara Salemba-Grogol. Kedua, masa akhirnya terpencar menjadi dua bagian besar, sebagian bergabung dengan lapangan Monas dan sebagian lainnya menuju Trisakti.
“Sulit bagi koordinator lapangan untuk mengidentifikasi mana mahasiswa yang telah memiliki kesepakatan koordinasi dan masa non-mahasiswa yang ikut tergabung tanpa mengetahui seluruh rencana,” tulis Eep Saefullah Fatah.
Masa yang berkumpul di Trisakti akhirnya bergerak memakai kendaraan ke pusat gerakan di lapangan Monas dan daerah seputar istana. Namun, unjuk rasa menjadi di luar kendali. Aksi damai menyampaikan Tritura itu berubah awut-awutan. Massa, entah dari kalangan mahasiswa koordinasi atau bukan, bertindak beringas dan menjadi anarkis.
Menurut pengakuan Panglima Komkaptip Jendral Soemitro kepada Tempo, seperti dinukil Caldwell dkk dalam Sejarah Alternative Indonesia (2011), pihaknya kemudian menemui massa untuk menenangkan kericuhan. Namun massa makin marah karena dirinya memakai mobil buatan Jepang. Dari mobilnya, Soemitro berjanji untuk melakukan audiensi antara mahasiswa dan Perdana Menteri Jepang Tanaka.
Massa kemudian menjawab bahwa mereka tak butuh dialog ruangan. Sebab sebelumnya mereka sudah bertemu Soeharto dan tanpa hasil apa pun. Soemitro juga sempat mengancam mahasiswa, pelaku pengrusakan dianggap sebagai pengkhianatan kepada negara. Namun ancaman itu tidak digubris. Dia kemudian menyuruh pasukan keamanan untuk menahan mahasiswa agar menjauhi istana.
Menurut Eep Saefullah Fatah, kerusuhan semakin melebar dengan aksi gabungan antara mahasiswa dan masyarakat, bukan lagi demonstrasi tapi jadi gerakan anti Jepang. Pengrusakan dan pembakaran kendaraan juga dilakukan tidak hanya milik pribadi. Kendaraan milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, kini TNI juga kena imbas. Kantor Astra yang terkenal sebagai importer Jepang termasuk show room turut diamuk massa.
“Termasuk perusahaan PT Insan Apollo, PT Subaru dan perusahaan lainnya. Mobil dan motor yang ada di daelar dirusak dan dihancurkan terutama mobil buatan Jepang,” tulis Eep Saefullah Fatah.
Menjelang sore, proyek Senen yang sudah dijaga aparat keamanan juga tak terselamatkan. Pusat pertokoan terbesar di Jakarta itu selain dirusak juga dijarah. Mobil pemadam kebakaran yang didatangkan tidak dapat berbuat banyak karena juga ikut dirusak. Malam harinya, sebuah menyebabkan aliran listrik terputus ke daerah itu. Gerakan anti Jepang kemudian meluas menjadi gerakan anti kemewahan dan kemaksiatan.
Usman Hamid dalam Penyelewengan Hukum dan Teror Propaganda (2013) mengungkapkan, menurut berbagai sumber, dalam kerusuhan 15 dan 16 Januari itu, 11 orang meninggal, 177 mengalami luka berat, 120 luka ringan dan 755 orang ditahan. Sementara itu 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak atau dibakar, 144 bangunan dan 1 pabrik rusak atau terbakar dan sejumlah 160 kilogram emas hilang dijarah.
Penyebab Peristiwa Malari
Ipong Jazimah dalam Malari: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru (2013) mengungkapkan percikan peristiwa ini telah bermula sejak 9 Januari 1974. Hari itu, sebelum kedatangan Tanaka, demonstrasi mahasiswa menentang keberadaan para asisten pribadi (aspri) presiden. Mereka menilai aspri Soeharto seolah memiliki kekuasaan yang besar melebihi pemerintah dan parlemen.
Kemudian pada 11 Januari, Soeharto menerima delegasi Dewan-Dewan Mahasiswa. Mereka menyampaikan kecaman dan mempertanyakan kewibawaan presiden yang dirongrong tingkah laku para pemimpin yang memperkaya diri secara tidak sah. Namun pertemuan antara delegasi mahasiswa dan Soeharto tidak menghasilkan apa-apa.
Dari situlah kemudian mahasiswa melalui sebuah Apel Siaga Mahasiswa di kampus UKI pada 12 Januari mengajak masyarakat untuk menyambut PM Jepang dengan gerakan aksi. Mereka mengajak masyarakat untuk memasang bendera setengah tiang pada hari kehadiran Perdana Menteri Tanaka.
“Selain itu juga mengajak koran untuk memboikot pemberitaan tentangnya, dan mengadakan aksi total pada tanggal 15 Januari 1974,” tulis Ipong.
Sebagai buntut peristiwa Malari 1974, polisi dan tentara menangkap banyak orang. Sebanyak 775 orang jadi pesakitan, termasuk para aktivis politik dan mahasiswa. Kepala Penerangan Departemen Pertahanan dan Keamanan Brigadir Jenderal Sumrahadi ketika itu mengatakan pemerintah terpaksa menahan orang-orang yang mereka curigai sebagai penggerak peristiwa Malari.
Pemerintah menuding ke berbagai arah. Sejumlah aktivis mantan anggota Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi dicurigai ada di balik aksi. Mengutip majalah Tempo dalam Edisi Khusus Malari, yang terbit 13 Januari 2014, angka itu terus menyusut dari waktu ke waktu. Pada pekan ketiga usai kerusuhan, jumlah pesakitan tinggal 300-an dan belakangan Cuma tersisa puluhan orang.
Kebanyakan dari mereka bebas karena kurang bukti. Pengacara Yap Thiam Hien dan wartawan Mochtar Lubis dilepas setelah setahun ditahan. Pengacara Adnan Buyung Nasution dibebaskan pada Oktober 1975 bersama sebelas mahasiswa, di antaranya Judilherry Justam, Theo Sambuaga, Bambang Sulistomo, Eko Jatmiko, Yessy Moninca, dan Remy Leimena.
Hanya Hariman dan Sjahrir dari Universitas Indonesia serta Aini Chalid dari Universitas Gadjah Mada yang disidangkan ke pengadilan. Mereka dituduh melakukan perbuatan subversi dan makar. Jaksa menggunakan pernyataan Hariman dan Sjahrir dalam sejumlah pertemuan Dewan Mahasiswa UI dan Gerakan Diskusi UI untuk menjerat keduanya sebagai koordinator lapangan dan otak peristiwa itu.
Dalam persidangan, sejumlah saksi menarik keterangannya di berita acara pemeriksaan. Ada yang mengaku tak sadar dan merasa terancam saat memberikan kesaksian. Beberapa yang lain tak tahu keterangannya digunakan untuk menjerat Hariman dan Sjahrir. Jaksa akhirnya bergantung pada informasi intelijen Operasi Khusus.
Meski tak cukup bukti menggerakkan kerusuhan, Hariman Siregar dijatuhi hukuman enam setengah tahun penjara pada 21 Desember 1974. Hakim menganggap kelalaiannya telah berujung pada aksi pembakaran dan perusakan. Kamis malam, 12 Juni 1975, majelis hakim yang dipimpin Anton Abdurrahman Putera menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara buat Sjahrir. Sedangkan Aini divonis 2 tahun 2 bulan.
“Kelalaian ini sama seperti kelalaian seseorang yang membeli arloji di pinggir jalan, padahal tahu di Jakarta sering ada penjambretan,” kata Siburian, seperti dikutip dari majalah Tempo edisi 28 Desember 1974 ihwal sidang kasus rusuh Malari itu.
Kakak Indra Purnama berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

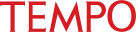 3 months ago
92
3 months ago
92










































