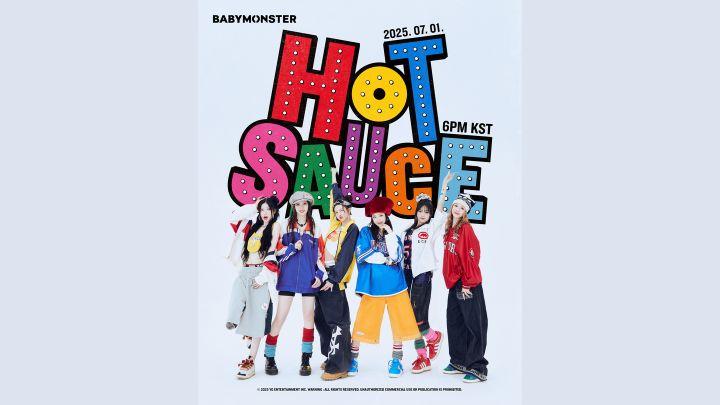(Beritadaerah-Kolom) Di tengah dinamika ekonomi dan kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat, industri sapi perah di Indonesia menjadi salah satu sektor yang cukup penting. Susu segar masih menjadi bahan pokok bagi jutaan rumah tangga dan juga bahan baku industri makanan dan minuman. Tapi bagaimana sebenarnya kondisi peternakan sapi perah kita sekarang?
Menurut laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik dalam buku Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah 2024, ada sebanyak 44 perusahaan sapi perah yang aktif beroperasi di Indonesia pada tahun 2024. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan-perusahaan ini tersebar di delapan provinsi dan sebagian besar berada di Pulau Jawa. Jawa Barat mencatat jumlah terbanyak, yaitu 19 perusahaan, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Sebagian besar dari perusahaan ini adalah bentuk badan usaha seperti PT, CV, atau firma. Sisanya adalah koperasi dan yayasan. Ini menandakan bahwa sektor ini tidak hanya dikelola oleh korporasi besar tapi juga oleh usaha kolektif masyarakat, seperti koperasi peternak.
Kegiatan utama dari perusahaan-perusahaan ini ada tiga. Pertama adalah budidaya sapi perah, kedua pembibitan sapi perah, dan yang ketiga adalah pengumpulan susu. Mayoritas perusahaan fokus pada budidaya, artinya mereka memelihara sapi betina untuk diambil susunya. Kegiatan pembibitan jumlahnya masih sedikit, ini menunjukkan bahwa produksi anak sapi masih belum menjadi perhatian utama.
Dari sisi tenaga kerja, industri ini menyerap hampir dua ribu orang pekerja, dengan mayoritas adalah laki-laki. Sebanyak 1.700 di antaranya merupakan pekerja tetap, dan sisanya adalah pekerja honorer atau pekerja harian. Ini juga menunjukkan bahwa industri peternakan sapi perah punya potensi membuka lapangan kerja tetap, walaupun dominasi pria masih terlihat kuat.
Lalu, bagaimana dengan jumlah sapinya? Pada akhir tahun 2024 tercatat ada sekitar 38 ribu ekor sapi perah yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan ini. Menariknya, lebih dari 98 persen dari jumlah ini adalah sapi betina. Dari jumlah tersebut, sekitar setengahnya belum masuk masa produksi, dan hampir setengahnya sedang aktif menghasilkan susu. Sisanya sedang dalam masa istirahat atau tidak produktif lagi.
Dari sapi-sapi betina yang sedang produktif, Indonesia berhasil memproduksi sekitar 163 juta liter susu segar sepanjang tahun 2024. Jumlah ini meningkat lebih dari 11 persen dibanding tahun sebelumnya. Sayangnya, peningkatan ini bukan karena produktivitas per ekor naik, melainkan karena jumlah sapi yang sedang menyusui memang bertambah. Justru produktivitas harian per ekor menurun sedikit dibanding tahun lalu, sekarang rata-rata hanya 28 liter per hari per ekor.
Meski begitu, secara keseluruhan sektor ini berhasil mencatat penerimaan mencapai hampir 1,8 triliun rupiah. Pengeluaran seluruh perusahaan juga cukup besar, yaitu sekitar 1,08 triliun rupiah. Artinya, masih ada keuntungan bersih sekitar 706 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa usaha peternakan sapi perah bisa tetap untung jika dikelola dengan baik.
Tapi ada satu catatan penting. Dari seluruh pengeluaran itu, lebih dari 73 persen digunakan untuk membeli pakan sapi. Biaya pakan menjadi yang paling besar, jauh mengalahkan biaya untuk gaji pekerja, listrik dan air, obat-obatan, atau bahan bakar. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada pakan masih tinggi dan menjadi tantangan utama bagi peternak sapi perah.
Selain susu, perusahaan juga menghasilkan pendapatan dari kotoran ternak, penambahan berat badan ternak, dan beberapa produk lainnya. Tapi kontribusi pendapatan dari sektor-sektor ini masih kecil dan belum dimaksimalkan.
Menariknya, data juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah sapi dari hasil kelahiran alami dibandingkan pembelian. Ini bisa menjadi sinyal positif bahwa beberapa perusahaan mulai mengandalkan regenerasi internal daripada impor sapi.
Namun, tantangan lain muncul dari produktivitas yang belum merata antar daerah. Jawa Timur misalnya bisa mencatat produksi susu harian per ekor mencapai lebih dari 30 liter, sementara provinsi lain seperti Sumatera Barat masih di bawah 13 liter per hari. Perbedaan ini bisa berasal dari kualitas pakan, manajemen peternakan, atau genetik sapi yang digunakan.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi industri ini yang masih terfokus di Pulau Jawa. Padahal kebutuhan susu tersebar di seluruh Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan insentif dan dukungan pemerintah agar peternakan sapi perah bisa tumbuh di luar Jawa. Infrastruktur, pasar, dan pelatihan tenaga kerja menjadi kunci penting.
Pemerintah dan pelaku industri juga bisa mulai mendorong diversifikasi usaha, seperti pengolahan susu menjadi produk olahan bernilai tambah, atau pemanfaatan limbah ternak menjadi kompos dan biogas. Selain bisa menambah pendapatan, langkah ini juga mendukung prinsip ekonomi sirkular dan ramah lingkungan.
Secara keseluruhan, industri peternakan sapi perah di Indonesia memang belum sebesar di negara-negara penghasil susu utama dunia. Tapi tren pertumbuhannya cukup positif. Jumlah perusahaan bertambah, produksi meningkat, dan pendapatan peternak juga naik.
Tantangannya kini adalah bagaimana menjaga keberlanjutan industri ini. Peternak harus terus didukung agar bisa menghasilkan susu dengan harga yang kompetitif, tanpa mengorbankan kualitas dan keberlangsungan usaha. Pemerintah pun diharapkan hadir dengan kebijakan yang pro-peternak, baik dari sisi insentif, subsidi pakan, hingga program pembibitan nasional.
Jika dikelola dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor susu dan menjadi negara mandiri dalam produksi susu segar. Jalan menuju swasembada susu memang tidak mudah, tapi data menunjukkan bahwa harapan itu masih sangat mungkin diraih.
Namun untuk mewujudkan swasembada susu, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama adalah soal ketergantungan pada pakan impor. Meskipun sebagian besar perusahaan menggunakan pakan hijauan dari dalam negeri, pakan konsentrat dan tambahan sering kali masih berasal dari luar. Selain mahal, ketergantungan ini juga membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi harga global.
Masalah berikutnya adalah regenerasi sapi. Hanya sedikit perusahaan yang fokus pada pembibitan. Padahal, untuk meningkatkan populasi sapi perah yang berkualitas, kegiatan pembibitan harus menjadi perhatian utama. Jika Indonesia bisa menghasilkan bibit sapi unggul sendiri, maka ketergantungan pada impor indukan dari luar negeri bisa ditekan. Ini akan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi jangka panjang.
Lalu, ada juga tantangan soal distribusi produk. Banyak peternak di daerah kesulitan menjual susu segar karena keterbatasan akses ke pasar atau kurangnya fasilitas pengolahan. Susu yang tidak langsung diserap industri sering kali harus dijual dengan harga rendah atau bahkan terbuang. Dalam hal ini, peran koperasi atau kemitraan dengan industri susu menjadi sangat penting.
Beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur memang sudah lebih maju dalam hal infrastruktur peternakan dan rantai distribusi. Tapi di luar Jawa, potensi besar seperti di Sumatera atau Kalimantan masih terkendala. Padahal, tanah yang luas dan kebutuhan pasar yang tumbuh bisa menjadi peluang besar jika ada dukungan serius dari pemerintah dan swasta.
Satu lagi persoalan yang sering muncul adalah rendahnya konsumsi susu di dalam negeri. Konsumsi susu per kapita Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Ini membuat permintaan terhadap susu lokal tidak berkembang secepat yang diharapkan. Padahal, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi, harusnya ada ruang pertumbuhan yang besar.
Untuk mengatasi hal ini, edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan. Kampanye minum susu nasional bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan permintaan. Bila konsumsi meningkat, maka industri peternakan sapi perah pun akan ikut tumbuh karena pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, peran pemerintah tidak bisa diremehkan. Regulasi yang mendukung, insentif untuk peternak, serta penyediaan akses kredit murah bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan industri ini. Misalnya, program bantuan pakan saat harga melonjak atau pelatihan teknologi peternakan modern untuk peternak kecil.
Penguatan koperasi peternak juga penting. Koperasi bisa menjadi sarana untuk menampung produksi, menyediakan pakan, menjual hasil ternak, hingga menjalin kerja sama dengan industri olahan. Dengan koperasi yang kuat, posisi tawar peternak kecil bisa meningkat, dan mereka tidak tergantung pada tengkulak atau perusahaan besar.
Sebagai gambaran, jika sebuah perusahaan sapi perah bisa menghasilkan susu dengan produktivitas tinggi, sekitar 30 liter per ekor per hari, maka mereka bisa bersaing secara ekonomi. Tapi kalau hanya menghasilkan 10–15 liter per hari seperti yang masih terjadi di beberapa provinsi, maka margin keuntungan menjadi sangat kecil.
Itulah mengapa teknologi peternakan menjadi kunci penting. Penerapan teknologi seperti mesin pemerahan susu otomatis, sistem pencatatan digital, hingga manajemen pakan berbasis nutrisi bisa membantu meningkatkan efisiensi. Tentu hal ini membutuhkan investasi, tapi pemerintah bisa hadir dengan program pembiayaan atau insentif.
Ada pula peluang dari sisi pengolahan. Tidak semua susu harus dijual dalam bentuk segar. Produk olahan seperti keju, yoghurt, susu bubuk, dan es krim justru punya nilai jual lebih tinggi. Jika perusahaan-perusahaan peternakan mulai masuk ke bidang ini, maka potensi keuntungannya akan meningkat.
Sebagian besar perusahaan saat ini masih menjual susu segar ke pabrik pengolahan besar. Ini sah-sah saja. Tapi ke depan, mereka bisa mulai membuat lini produk sendiri, bahkan dengan merek lokal. Konsumen sekarang juga semakin tertarik pada produk yang transparan, sehat, dan berasal dari peternakan yang ramah lingkungan.
Konsep peternakan berkelanjutan atau green dairy farm juga mulai dilirik. Misalnya, penggunaan biogas dari kotoran ternak untuk energi, atau pemanfaatan limbah sebagai pupuk. Tidak hanya efisien, tapi juga menarik minat pasar yang sadar lingkungan.
Kabar baiknya, tren global kini mulai berpihak pada sistem produksi yang lokal, etis, dan berkelanjutan. Peternakan sapi perah Indonesia bisa menyesuaikan diri dengan tren ini. Bahkan, jika kualitas produk terus membaik, bukan tidak mungkin produk susu Indonesia bisa masuk ke pasar ekspor.
Melihat perkembangan dalam laporan BPS, sebenarnya sudah banyak kemajuan. Jumlah perusahaan bertambah dari tahun ke tahun. Tahun 2021 ada 33 perusahaan aktif, kemudian naik menjadi 34 pada 2022, 37 pada 2023, dan akhirnya 44 perusahaan aktif pada 2024. Artinya, ada kepercayaan pasar dan pelaku usaha terhadap industri ini.
Pekerja pun bertambah. Pada 2021 hanya sekitar 1.000 orang yang bekerja di sektor ini, kini hampir 2.000 orang. Ini menunjukkan bahwa peternakan sapi perah bukan hanya menyumbang pangan, tapi juga membuka lapangan kerja.
Dari sisi keuntungan, tren positif juga terlihat. Tahun 2021 keuntungan total dari sektor ini mencapai sekitar 479 miliar rupiah. Tahun 2022 turun jadi 270 miliar, tapi kemudian naik drastis di 2023 dan menembus 706 miliar rupiah pada 2024. Ini membuktikan bahwa sektor ini punya daya tahan yang kuat meski ada tantangan.
Sektor peternakan sapi perah Indonesia bisa semakin kuat jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, peternak kecil, koperasi, dan konsumen. Masing-masing punya peran. Pemerintah membuat kebijakan dan memberikan dukungan. Pengusaha membawa inovasi dan investasi. Peternak menjaga kualitas dan keberlanjutan produksi. Dan konsumen mendukung produk lokal.
Dengan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin suatu saat nanti kita bisa melihat Indonesia sebagai negara yang tidak hanya cukup susu untuk konsumsi dalam negeri, tapi juga bisa mengekspor produk-produk susu berkualitas tinggi ke negara lain.
Mimpi itu bukan hal yang mustahil. Industri sapi perah kita memang masih bertumbuh, tapi pondasinya sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana semua pihak bekerja bersama, membangun dari peternakan yang kecil hingga sistem distribusi dan pengolahan yang terintegrasi.
Peternakan sapi perah tidak hanya soal sapi dan susu. Ini soal ketahanan pangan, kesejahteraan peternak, gizi masyarakat, dan kedaulatan bangsa. Jika kita mampu memperkuat sektor ini, maka kita sedang berinvestasi pada masa depan yang lebih sehat, mandiri, dan berdaya.