TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa penetapan darurat militer di Korea Selatan, Selasa tengah malam, 3 Desember 2024 mengingatkan warga negara tersebut akan tragedi 44 tahun yang lalu, Tragedi Gwangju.
Dalam sebuah pidato mendadak pada malam hari, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer.
Ia mengklaim bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk menghadapi gerakan dari Partai Demokratik yang berfungsi sebagai oposisi, yang telah mempengaruhi agenda pemerintah. Namun, keputusan ini dengan cepat menghadapi penolakan dari anggota parlemen dan masyarakat.
Darurat Militer
Dalam pengumuman yang mengejutkan, Yoon Suk-yeol mendeklarasikan darurat militer sambil menuduh Partai Demokratik bersekongkol dengan Korea Utara dan terlibat dalam kegiatan anti-negara. Ia mengerahkan pasukan militer dan polisi ke gedung National Assembly, lengkap dengan penerbangan helikopter yang terlihat mendarat di atap gedung tersebut.
Namun, tidak lebih dari dua jam setelah pengumuman darurat itu, para anggota legislatif berhasil menerobos barikade yang dijaga oleh tentara dan secara bulat membatalkan keputusan tersebut dalam sidang darurat.
Dikutip dari Al Jazeera, dengan 190 dari 300 anggota hadir, pengesahan ini mencerminkan kekuatan demokrasi yang masih hidup di Korea Selatan. Yoon pun terpaksa menerima keputusan tersebut, yang menandai penolakan masyarakat terhadap tindakan yang dianggapnya sebagai pelanggaran konstitusi.
Seiring dengan situasi yang tegang ini, ribuan warga turun ke jalan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka, meskipun kehadiran militer tidak menyebabkan kekerasan. Masyarakat sipil secara tegas menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan sejarah kelam terulang kembali.
Kilas Balik Tragedi Gwangju 1980
Tragedi Gwangju 1980 dimulai pada 18 Mei ketika protes damai oleh mahasiswa di Universitas Chonnam melawan pemberlakuan darurat militer juga ditindak dengan brutal oleh pemerintah. Protes tersebut mencerminkan ketidakpuasan yang mengakar dalam masyarakat terhadap pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Chun DooHwan setelah kudeta militer.
Di tengah berlangsungnya demonstrasi, pasukan militer dikerahkan untuk menekan protes, dan peristiwa ini dengan cepat berubah menjadi suatu pemberontakan besar. Masyarakat Gwangju, yang sudah lama merasa tertekan, mulai bersatu dalam perlawanan.
Ketika presidium dipindahkan ke pusat kota, para demonstran melawan dengan semua yang mereka miliki, dari bat hingga senjata seadanya. Sayangnya, perlawanan tersebut ditanggapi dengan kekerasan yang amat brutal.
Dalam waktu singkat, militer menggunakan tank dan helikopter untuk menyerang kota, menghancurkan harapan untuk kebebasan dengan kekerasan. Meskipun pemerintah pada awalnya mencatat jumlah korban jiwa sebanyak 200 orang, menurut Britannica, banyak warga lokal memperkirakan jumlah sebenarnya mendekati 2.000 jiwa.
Gwangju tidak berhasil dalam membawa demokrasi saat itu, namun peristiwa ini menjadi simbol tekad masyarakat Korea Selatan untuk melawan penindasan. Kenangan akan perjuangan Gwangju terus hidup dalam ingatan kolektif rakyat, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga kebebasan dan hak asasi manusia.
Saat masyarakat Korea Selatan menyaksikan perkembangan baru dengan deklarasi darurat militer oleh Yoon Suk Yeol, banyak yang merasakan ketakutan dan deja vu mengenang kembali peristiwa 1980. Mereka yang selamat dari tragedi tersebut, kini memandang peristiwa ini sebagai alarm untuk melawan kembali, tidak membiarkan sejarah berulang dan melupakan perjuangan yang telah dilalui.
Perlawanan yang terjadi belakangan ini bukan hanya sebuah reaksi terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya demokrasi yang diperjuangkan dengan nyawa banyak orang.
Dalam menghadapi situasi ini, warga Korea Selatan menunjukkan kebersamaan untuk melindungi hak-hak mereka, mengingat apa yang telah terjadi di Gwangju dan bertekad untuk tidak membiarkan tragedi serupa terulang kembali.

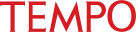 3 months ago
103
3 months ago
103













































