PADA hari pertamanya menjabat sebagai Menteri Koordinator, Yusril Ihza Mahendra, mengeluarkan pernyataan yang disorort berbagai pihak tentang keseriuan pemerintahan Prabowo tangani penegakan HAM atau Hak Asasi Manusia. Ia mengatakan bahwa peristiwa kekerasan pada 1998 bukan merupakan pelanggaran HAM berat.
Menurut Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Collective for Critical Legal Studies (Colleges), Markus Togar Wijaya, pernyataan Yusril tersebut koheren dengan kenyataan bahwa tak ada secuil komitmen Prabowo Subianto terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
"Sikap ini menjadi indikasi bahwa Indonesia memasuki zaman kegelapan. Zaman ini sebagai dark ages of human rights," kata Markus.
Pernyataan itu, menurutnya, menunjukkan bahwa Yusril enggan membaca literatur ilmiah yang menyoroti pelanggaran HAM berat di Indonesia. Padahal, ada banyak literatur nasional dan internasional yang menunjukkan bagaimana infrastruktur kekuasaan bekerja untuk membungkam, menyabotase, dan membunuh HAM.
Dark Ages of Human Rights
Dark ages of human rights yang dimaksud Markus, ditandai dengan munculnya sejumlah penalaran amburadul tidak bersandar pada keilmiahan yang persis, seperti pernyataan Yusril Ihza. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini dikesampingkan. Bahkan, ilmu pengetahuan dimusnahkan dalam proses pengambilan kebijakan. Puncak dari kondisi ini adalah dunia terjebak dalam kegelapan dan berujung pada pembodohan publik.
"Kondisi ini terjadi karena kebanyakan pejabat hanya paham HAM sebatas yang tercantum dalam konstitusi. Padahal, makna HAM jauh lebih dalam daripada itu. Menegakkan HAM bukan hanya sekadar menyediakan segala kebutuhan warga negara, melainkan juga memanusiakan seorang manusia," kata Markus kepada Tempo.co, Rabu, 15 Januari 2025.
Menurut Markus, pemahaman mendasar ini juga luput dari Menteri HAM Indonesia, Natalius Pigai. Ia mengatakan bahwa kementerian HAM memerlukan anggaran Rp20 triliun untuk pembangunan HAM. Markus menilai, perkataan Pigai ini berada diluar nalar keilmiahan dan tidak bersandar pada realitas sosial. Sebagai warga negara, seharusnya patut curiga dan kritis. Kemana dana tersebut akan mengalir? Bagaimana potensi penyelewengannya? Apakah implementasinya akan berjalan mulus? Dan bagaimana potensi konflik kepentingan yang ditimbulkan?
Lebih lanjut, Pigai juga mengatakan keinginannya merancang pembangunan universitas HAM, laboratorium HAM, dan rumah sakit HAM. Menurut Markus, keinginan ini mengindikasikan bahwa era pembangunan infrastruktur yang dibalut dengan label “hak asasi manusia” sebagai alasan pembenar mulai muncul. Namun, kondisi ini bisa mendatangkan bahaya karena frasa HAM dijadikan sebagai ladang ekonomisasi untuk melicinkan proyek-proyek oligarki demi mendulang profit.
Markus dalam catatannya menegaskan, terdapat permasalahan dari pernyataan Pigai tersebut. Sebelum Pigai mengeluarkan pernyataan tentang pembangunan infrastruktur HAM, apakah sudah melakukan riset ilmiah terlebih dahulu? Apakah ia sudah mengadakan jajak pendapat tentang kebutuhan masyarakat? Apakah ia sudah memahami secara utuh problematika HAM di Indonesia? Oleh karena itu, Pigai lebih baik memfokuskan Kementerian HAM pada penyelesaian kasus-kasus HAM yang tidak kunjung tuntas daripada berambisi membangun infrastruktur diluar tupoksi kementerian. Selain itu, masih banyak juga masyarakat terlibat konflik agraria berbasis kekuatan militer yang meregang nyawa, tewas tertembak aparat.
Tak hanya itu, dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat, mata rantai impunitas juga semakin kuat. Mereka—para penjahat HAM—masih berada “di atas hukum” dan tidak tersentuh. Kondisi ini melahirkan pertanyaan, mengapa Pigai tidak fokus mengurusi masalah ini saja? Apakah ia lupa, bahwa Aksi Kamisan telah bertahun-tahun berdiri teguh di depan istana negara dan menuntut untuk mengadili para penjahat HAM?
Jawaban dari pertanyaan tersebut karena Kementerian HAM hanya mengikuti kemauan “majikannya” yang tidak memiliki visi tentang penegakan HAM. Jawaban ini sama dengan ungkapan Jokowi yang nampaknya masih dilestarikan Prabowo: tak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden.
Markus melihat bahwa benang merahnya terbaca jelas. Pada penegakan HAM, warga negara hanya akan dianggap sebagai objek, bukan subjek yang dilibatkan secara aktif. Kementerian HAM tidak akan berani melibatkan warga negara sebagai subjek karena rentan mengikis posisi politik “majikannya”. Meskipun kelak Prabowo menggagas kembali mekanisme penyelesaian HAM non-yudisial, seperti Jokowi yang membentuk Tim PPHAM, ini tidak akan menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia.
"Ide penyelesaian HAM secara non-yudisial adalah bentuk keputusasaan negara untuk mengadili penjahat HAM melalui jalur yudisial (pengadilan). Berdasarkan Keppres 17/2022 yang diteken Jokowi untuk membentuk Tim PPHAM sangat sarat kepentingan politik yang dalam praktiknya berujung pemecahan gerakan sosial," kata dia.
Lantas, bagaimana dengan lembaga pengadilan? Baru-baru ini, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengajukan gugatan terhadap pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan untuk Prabowo. Namun, ada keanehan bahwa dalam Putusan Nomor 186/G/2024/PTUN.JKT., Hakim PTUN Jakarta justru menilai penggugat tidak memiliki legal standing. Artinya, Hakim PTUN Jakarta cenderung ingin memisahkan (membela) Prabowo dari kasus Penghilangan Secara Paksa 1997-1998.
Kondisi tersebut tidak mengagetkan. Sebab, Rosser pada 2013 telah menuliskan dalam risetnya bahwa sistem peradilan dan Kejaksaan Agung telah bertindak korup dan tidak efisien. Akibatnya, sistem peradilan dan Kejaksaan Agung justru menjadi lembaga yang mempromosikan impunitas. Dengan demikian, kondisi ini juga memengaruhi penegakan HAM di Indonesia yang hanya menjadi retorika.
Pilihan Editor: Mahfud Md Sebut Upaya Penegakan HAM Tidak Selalu Berjalan Mulus

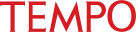 1 month ago
30
1 month ago
30













































