TEMPO.CO, Jakarta -Tale of the Land, karya terbaru besutan sutradara Loeloe Hendra ditayangkan perdana di Busan International Film Festival 2024. Film berdurasi 1 jam 39 menit ini mengantongi FIPRESCI Award, penghargaan prestisius dari Federasi Internasional Kritikus Film, sebuah pengakuan atas bahasa visual yang memukau dalam membahas isu penting tentang rusaknya harmoni antara manusia dan alam, serta referensi budaya tradisional.
Mengusung genre thriller-drama, film ini mengajak penonton menyelami kehidupan May (Shenina Cinnamon), seorang gadis Dayak yang terkungkung trauma dan realitas konflik agraria di Kalimantan. Loeloe membawa penonton menyelami lapisan-lapisan persoalan manusia, lingkungan, dan tradisi yang kian terkikis oleh modernitas.
Rumah Apung dan Benang Merah Konflik Agraria
Dibuka dengan visual rumah apung di tengah danau, Loeloe meramu simbolisme sejak menit pertama. May tinggal bersama kakeknya (Arswendy Bening Swara) di rumah terapung yang hampir karam diterpa ombak. Pertanyaan sederhana May kepada sang kakek—mengapa mereka tidak pindah—mencuatkan tema besar dalam film, yakni keterikatan pada masa lalu dan ketakutan menghadapi dunia baru.
Dengan dialog berbahasa Kutai, trauma May pertama kali diperkenalkan: ia tidak bisa menginjakkan kaki di tanah akibat tragedi yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Kematian mereka terbungkus dalam konflik agraria yang masih menjadi luka kolektif masyarakat lokal.
Salah satu adegan juga menunjukkan saat jukung kecil milik sang kakek dengan tenang menepi, menyaksikan tongkang raksasa yang mengangkut gunungan batu bara melintas di perairan tempat tinggal mereka. Melalui adegan tersebut, film ini secara halus menggambarkan nasib masyarakat adat yang semakin terpinggirkan dan terhimpit oleh laju modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Review Film Tale of The Land: Visual Kelam dan Narasi Non-Linear
Sinematografi film ini layak mendapat pujian. Dengan palet warna tone down yang didominasi biru kelam dan abu-abu, visualnya seolah berbicara tentang suramnya kehidupan May dan sang kakek yang digerus eksploitasi. Adegan malam hari, ketika May mendengar suara kerbau dari kejauhan dan mendapati seekor anak kerbau di rumahnya, juga memadukan intrik surealis. Sosok kerbau seolah menjadi metafora tentang jiwa yang terbelenggu, baik May maupun leluhurnya.
Pendekatan khas film arthouse atau film seni, nampak dalam narasi non-linear dan minim dialog. Penonton diajak menafsirkan sendiri makna dari deretan peristiwa yang ditampilkan; mulai dari adegan kakek menyembelih ayam cemani dan mengoleskan darahnya ke kaki May sebagai perlindungan spiritual, hingga momen May mencoba mendekat ke darat dan selalu terjatuh. Elemen-elemen ini tak hanya menghadirkan konflik batin May, tapi juga membingkai hubungan manusia dengan tradisi dan alam.
Tradisi, Eksploitasi, dan Pencarian Identitas
Hubungan May dengan kakeknya juga menjadi poros dalam film tersebut. Sang kakek mencerminkan generasi yang mengandalkan tradisi untuk bertahan. Ia melarang May pergi ke daratan, menyebutnya sebagai tempat terkutuk yang telah dirusak tambang. May, dengan segala gelisahnya, terus mendengar panggilan tanah—sebuah simbol bahwa trauma dan keinginan untuk sembuh sering kali bertentangan.
Salah satu adegan paling magis adalah ketika May menari dengan kostum Dayak. Dibalut busana putih dan bulu-bulu elang di jarinya, ia bergerak dengan luwes, seakan menyatu dengan alam. Tarian ini seolah menjadi metafora kebebasan yang selalu ia rindukan, namun tak pernah sepenuhnya diraih May.
Ketegangan mencapai puncaknya saat sang kakek terluka akibat konflik agraria yang kembali memanas. Adegan ini memperlihatkan bagaimana eksploitasi tambang tidak hanya merusak tanah, tapi juga kehidupan manusia. Ketika sang kakek berpulang akibat konflik di darat, tarian May bertransformasi menjadi elegi. Dalam iringan petikan gitar khas Kalimantan—disebut Sape, adegan ini menciptakan momen yang semakin merangkum kepedihan film.
Tale of the Land ditutup dengan adegan May yang seorang diri mencoba pergi ke darat, langkahnya terhenti tanpa jawaban, menjadi simbol perlawanan sekaligus pertanyaan tentang nasib May dan masyarakat setempat. Film ini tidak menawarkan penyelesaian yang mudah, namun memberikan ruang untuk berefleksi tentang hubungan manusia dengan tradisi, eksploitasi, dan mereka yang terjebak di antaranya.

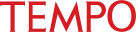 3 months ago
104
3 months ago
104












































